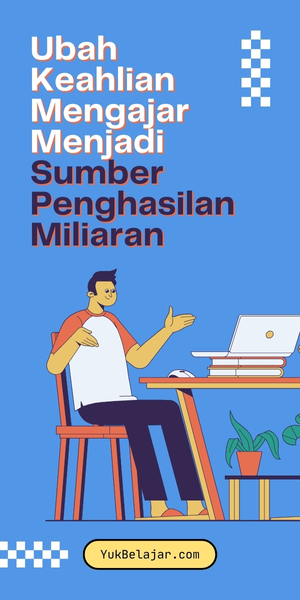Belajar Melambat Di Era Serba Cepat, Catatan Seorang Mahasiswa


Dalam kehidupan kampus yang sering seperti perlombaan tanpa garis akhir, saya pernah merasa bahwa bergerak cepat adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Tugas datang bertubi-tubi, aktivitas organisasi berjalan berlapis, dan media sosial terus menampilkan pencapaian orang lain seolah waktu tidak boleh terbuang. Namun, suatu titik jenuh justru mengubah cara saya memandang ritme hidup. Dari situ saya belajar melambat, dan pelajaran itu menjadi titik balik yang membentuk cara saya menjalani kuliah hingga hari ini.
Mengapa Saya Merasa Harus Selalu Cepat
Pada awal masa kuliah, saya mengira produktivitas hanya diukur dari seberapa banyak hal yang saya lakukan. Semakin sibuk, semakin “berharga” rasanya. Saya mengikuti banyak kegiatan sekaligus, rela mengorbankan tidur, dan memaksakan diri untuk selalu tampil maksimal. Sayangnya, semakin cepat saya berlari, semakin kabur arah yang ingin saya tuju.
Di antara jadwal yang padat, saya mulai kehilangan ruang untuk berpikir. Saya belajar bahwa kecepatan sesungguhnya bukan hanya soal laju, tetapi kemampuan menjaga kendali. Ketika hidup terasa seperti mobil yang dipacu tanpa rem, kerusakan hanya tinggal menunggu waktu.
Saat Tubuh Meminta Saya Berhenti
Puncaknya terjadi ketika saya mulai sering jatuh sakit dan tidak mampu fokus, bahkan pada tugas yang paling sederhana. Pada titik itulah saya benar-benar berhenti dan bertanya: untuk apa semua ini? Apakah saya melakukan banyak hal karena keinginan pribadi atau hanya karena takut tertinggal?
Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Namun justru di fase melambat inilah saya menemukan perspektif baru. Saya menyadari bahwa produktivitas bukan soal kecepatan, tetapi keseimbangan. Melambat bukan berarti mundur, justru memberi ruang untuk melihat lebih jelas apa yang penting dan apa yang hanya membuat lelah.
Menemukan Ritme Belajar yang Lebih Manusiawi
Saya mulai mengatur ulang rutinitas: mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan jangka panjang, memberikan jeda di antara tugas, dan membatasi konsumsi layar. Pada awalnya, perubahan ini terasa aneh. Namun perlahan saya mulai memahami bahwa ritme yang stabil jauh lebih bermanfaat daripada ritme yang cepat tetapi melelahkan.
Saya juga mulai merasakan kembali kenikmatan belajar. Membaca jurnal tanpa terburu-buru, mengerjakan tugas dengan fokus penuh, hingga berdiskusi dengan teman tanpa tekanan waktu—hal-hal kecil itu membuat proses belajar terasa hidup.
Dampak Melambat pada Cara Saya Melihat Dunia
Ketika ritme hidup berubah, cara saya memandang sekitar pun ikut bergeser. Saya melihat bahwa banyak mahasiswa yang mengalami hal serupa: mengejar ekspektasi, membandingkan diri, dan takut tertinggal. Kita hidup di kultur kampus yang secara tidak langsung mendorong kecepatan, padahal tidak semua orang bekerja dengan ritme yang sama.
Melambat mengajarkan saya untuk melihat kedalaman, bukan hanya kecepatan. Saya mulai lebih menghargai proses, lebih peka pada diri sendiri, dan lebih bijak dalam memilih prioritas. Alih-alih berfokus pada hasil tercepat, saya belajar menikmati perjalanan yang utuh.
Mengapa Mahasiswa Perlu Belajar Melambat
Melambat bukan tentang malas atau menunda. Ini tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, berpikir, dan bertumbuh. Dalam kehidupan akademik yang penuh tekanan, kemampuan melambat bisa menjadi bentuk keberanian—keberanian untuk memilih ritme yang sehat, bukan ritme yang dipaksa lingkungan.
Mahasiswa memang dituntut untuk bergerak, tetapi juga perlu tahu kapan harus berhenti dan mengevaluasi. Justru dari jeda itulah kita dapat melangkah lebih mantap.
Jika saya tidak pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk melambat, mungkin saya masih berlari tanpa arah hingga sekarang. Dan justru dari proses ini, saya memahami bahwa perjalanan kuliah bukan sprint, melainkan marathon. Yang paling penting bukan siapa yang tercepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan hati yang tetap utuh.
Tentang Penulis

0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini
Tulis Komentar
Lagi Tranding
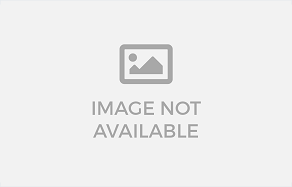
Rekomendasi Lainnya
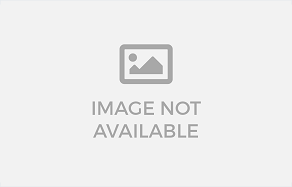
Rekomendasi Trending

UnivDay SMA Negeri 1 Cirebon: Alumni Lintas Generasi Menginspirasi 432 Siswa Kelas 12 Menyongsong Masa Depan

PMB STIKOM El Rahma Resmi Dibuka, Menawarkan Program Sarjana Komputer, Program Studi Informatika

3 Langkah Cerdas Mulai Karir Di Dunia Digital Bersama STIKOM El Rahma

Mengenal Program Studi Di Perguruan Tinggi Dan Prospek Masa Depannya

Mahasiswa Indonesia Dan Kecerdasan Buatan AI: Peluang Dan Tantangan Dalam Dunia Akademik

Peran Mahasiswa Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

Peran Strategis Ikatan Bidan Indonesia Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Era Digital

Gelar Rapat Perdana, Mata Garuda LPDP Jawa Tengah 5.0 Mengawali Babak Kepengurusan Baru
Tagar Populer
Rekomendasi Terbaru

ANVESHAKA: University Day SMANSA 2025 Hadirkan Alu...

Mengenal Jurusan Manajemen Bisnis Syariah: Pengert...

UnivDay SMA Negeri 1 Cirebon: Alumni Lintas Genera...

Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Dalam Masyarakat

Mahasiswa Dan Kesiapan Menghadapi Dunia Kerja

Mahasiswa Dan Literasi Akademik Dalam Dunia Pergur...

Mahasiswa Dan Tantangan Manajemen Waktu Di Perguru...