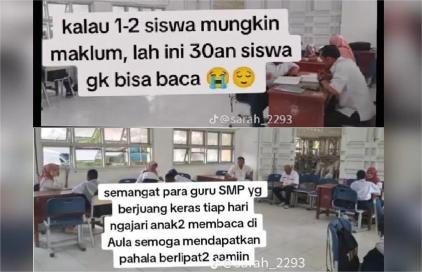Apakah ‘Healing’ Mahasiswa Benar-Benar Menyembuhkan? Fenomena Istirahat Yang Jadi Tren Baru Di Kampus


Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “healing” menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Pergi ke café estetik, liburan singkat, staycation, hingga sekadar jalan sore dianggap sebagai cara memulihkan diri dari tekanan kuliah. Unggahan photo dump atau video ‘healing day’ pun semakin mendominasi media sosial. Namun muncul pertanyaan penting: apakah healing benar-benar menyembuhkan, atau hanya pelarian sesaat dari realita akademik?
Tekanan Kuliah yang Membuat Healing Terasa Perlu
Tidak bisa dipungkiri, mahasiswa hari ini menghadapi tekanan besar. Tugas padat, deadline beruntun, kegiatan organisasi, proyek kampus, hingga persaingan akademik sering membuat kesehatan mental menurun. Banyak mahasiswa merasa perlu mengambil jeda agar tidak mengalami burnout. Healing kemudian menjadi solusi paling cepat, paling mudah, dan paling dapat diterima secara sosial. Istirahat bukan lagi dianggap malas, tetapi bentuk perawatan diri.
Ketika Healing Berubah Menjadi Tuntutan Sosial
Menariknya, tren healing juga menciptakan standar sosial baru. Banyak mahasiswa merasa “harus” healing agar terlihat peduli diri sendiri. Fenomena ini membuat sebagian orang justru memaksakan diri pergi healing meski kondisi finansial atau mental tidak mendukung. Ada pula yang merasa healing harus terlihat estetik demi diunggah di media sosial. Paradoks pun muncul: healing yang seharusnya menyembuhkan malah menjadi sumber stres tambahan karena tuntutan visual dan ekspektasi sosial.
Jeda Emosional yang Dibutuhkan, Bukan Sekadar Agenda
Healing sebenarnya bukan tentang lokasi atau aktivitas tertentu, melainkan tentang memberi ruang untuk jeda emosional. Ada mahasiswa yang pulih dengan tidur cukup, membaca buku, atau ngobrol dengan teman dekat. Ada pula yang merasa segar kembali setelah membersihkan kamar atau menonton film di rumah. Namun tren populer membuat definisi ini menjadi sempit, seolah healing harus dilakukan di luar rumah dan harus didokumentasikan. Padahal inti healing adalah mendengarkan kebutuhan diri, bukan mengikuti arus tren.
Pentingnya Membedakan Antara Self-Care dan Self-Escape
Fenomena healing memperlihatkan batas tipis antara perawatan diri dan pelarian diri. Jika healing dilakukan untuk menghindari tugas, masalah, atau tanggung jawab, maka manfaatnya hanya sementara. Setelah kembali ke rutinitas, beban justru terasa lebih berat. Sebaliknya, jika healing dilakukan sebagai bentuk pengaturan energi, mahasiswa dapat kembali menjalani aktivitas dengan kepala lebih jernih. Inilah yang membuat kemampuan mengenali batas diri menjadi skill yang sangat penting di era penuh tekanan seperti sekarang.
Pada akhirnya, healing tetap dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa. Namun healing tidak harus mahal, tidak harus estetik, dan tidak harus mengikuti tren. Mahasiswa yang mampu memahami makna istirahat yang sesungguhnya akan lebih mudah menemukan keseimbangan antara produktivitas, kesehatan mental, dan kehidupan akademik mereka.
Tentang Penulis

0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini
Tulis Komentar
Lagi Tranding

Rekomendasi Lainnya

Rekomendasi Trending

Bandung Heritage Green Fair 2025

Pemanfaatan AI Dalam Dunia Pendidikan Antara Inovasi Dan Tantangan Etika
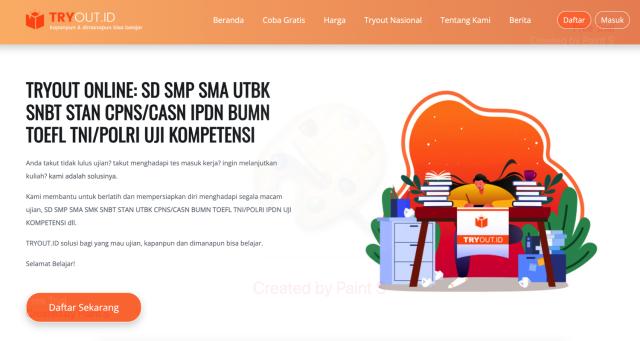
Tes Masuk BUMN: Maksimalkan Peluang Lolos Dengan Latihan Soal Dan Tryout Online Di TRYOUT.ID

Jasa Review Produk: “Word Of Mouth” Di Era Digital Bersama Blogger
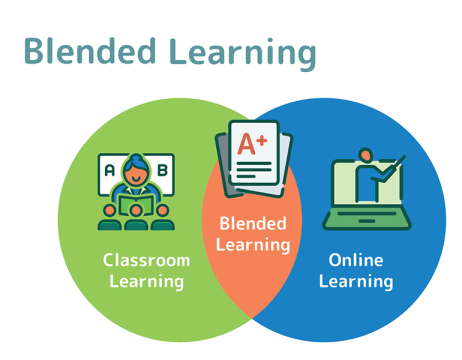
Penerapan Metode Blended Learning Dalam Pendidikan Modern Tingkatkan Kemandirian Dan Efektivitas Belajar

Cara Kuliah Sambil Kerja Agar Tetap Produktif Dan Lulus Tepat Waktu

Ma’soem University Jalin Kolaborasi Strategis Dengan BRIN Untuk Perkuat Ekosistem Riset Dan Inovasi Nasional

Mahasiswa Dan Fenomena “Quarter Life Crisis”: Peran Kampus Dalam Membangun Mental Tangguh Generasi Z
Tagar Populer
Rekomendasi Terbaru

Rapat Dengar 2025 Universitas Ma’soem: Menguatkan...

Mengapa Mahasiswa Mudah Tertekan?

Mengapa Mahasiswa Terlihat Sibuk, Tapi Tidak Produ...
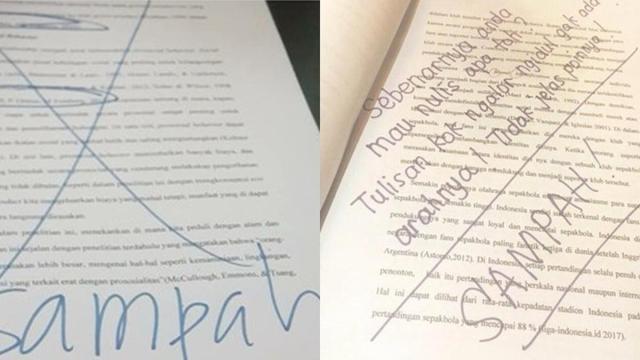
Cara Menghindari Revisi Berulang: Strategi Menyusu...

Rahasia Menyusun Tesis Lebih Cepat, Teknik Riset Y...

Cara Menyelesaikan Skripsi Tanpa Drama

Apakah Mahasiswa Perlu Punya Personal Branding? Ke...